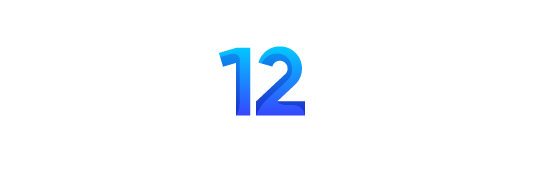Catatan tentang silaturahim dari Kera Ayabarus Panji Dwi Anggara (Blasteran Padang – Madura),
Malam mulai larut saat kami meninggalkan Surabaya. Badan letih, namun mata tak jua bisa terpejam. Bukan, bukan karena berisiknya suara roda kereta api yang menderu. Bukan pula karena dinginnya AC di gerbong nomor 7 itu. Melainkan karena bayangan pulang kampung.
Mudik, atau pulang kampung memang memiliki daya magis yang kuat. Panggilannya seolah membuat diri ini telah sampai di tempat tujuan, meski raga masih terduduk manis di perjalanan.
Sudah lebih dari 8 tahun kami tak pulang bersama. Komplit, satu keluarga. Wajar kalau antusiasme itu begitu meledak di hati.
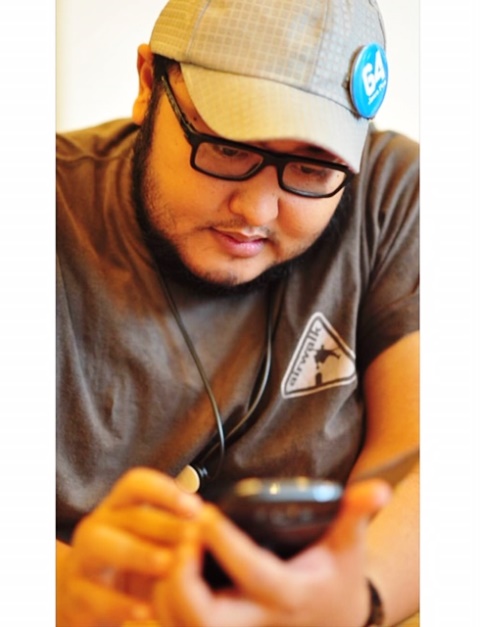
Perjalanan menggunakan kereta malam adalah awal bagi kami. Jika biasanya Jakarta adalah destinasi terakhir, kini Ibu Kota itu hanya sekadar tempat transit. Perjalanan kami masih panjang. Ribuan kilometer lagi.
Bumi Andalas, Sumatera, cuilan surga yang diletakkan Allah di muka bumi lah yang menjadi tujuan kami.
Padang, Lubuk Basung, Bukittinggi, dan Jambi adalah kepingan puzzle yg membentuk watak kami dari garis ayah. Selain tentunya darah Sumenep, Madura yg juga mengalir deras.
Empat kota di atas tak asing. Dulu, ketika saya masih kecil, hampir tiap dua tahun sekali kami pulang kampung.
Empat kota di atas juga tak asing bagi ibu kami yang keturunan Sumenep tulen. Sebab, di masa mudanya, Mami lama menghabiskan waktu di Minangkabau. Ikut orangtuanya yang kebetulan menjadi Direktur PT Garam.
Jadi, meskipun Papi -yg notabene berdarah Padang- sudah wafat, tidak mengurangi rasa rindu kami pada kampuang halaman.
Adzan dari surau tua tetap sama terdengar meski mungkin sang muadzin telah berganti. Aroma tanah yang tersapu air hujan tetap sama tercium meski mungkin menyisakan kelu. Dan, rasa rendang itu tetap sama enaknya, selalu ada cinta di setiap gigitan.
Panggilan pulang kampung membuat kami tersenyum sepanjang perjalanan. Bukan tak ada halangan, namun benar, perjalanan akan membuat hubungan menjadi jauh lebih bermakna. Di situ kami mengetahui, ini yg namanya keluarga.
Lepas Jakarta, Jambi adalah kota tujuan pertama. Kota dimana Papi dilahirkan. Kota dimana bersemayam jasad para leluhur. Kota dimana banyak orang-orang tercinta tinggal. Terima kasih tak terhingga untuk semua keluarga di sana.
Terima kasih untuk nasi padangnya, terima kasih untuk pempek dan tekwannya, terima kasih untuk jasa guidenya, terima kasih untuk es kacang merah yang juara, dan yg terpenting terima kasih untuk kebersamaan serta waktu yg diluangkan.
Usai Jambi, giliran Padang yang kami jamah. Bukit barisan yang kokoh berdiri seolah memberikan sambutan tersendiri. Banyak cerita yang tercatat dari lereng Merapi, hingga nun jauh di Danau Maninjau. Tempat si Bung Besar Soekarno mengaku keturunan Sumatera.

Masih tersimpan jelas sajak yang beliau ciptakan.
“Jika Adik Memakan Pinang
Makanlah dengan sirih yang hijau.
Jika Adik datang ke Minang
Jangan lupa datang ke Maninjau.”
Ranah Minang memang diciptakan ketika Allah tersenyum. Bukti keesaannya terlihat jelas di sana.
Pulanglah, pulang.
Dengan pulang, kita bisa berdamai dan berperang dgn diri sendiri.
Berdamai dgn masa lalu yg tak semuanya indah.
Berperang dgn kenaifan yg telah kita perbuat saat ini. Bukankah saat kecil dulu kita sudah diberi nasehat tentang benar dan salah. Tidak ada grey area. Semua serba hitam putih. Ini yg dinamakan : introspeksi diri.
Pulanglah, pulang.
Mengutip syair Ebiet G Ade, dengan pulang kita tahu, saudara yang dulu berbahu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk.
Dengan pulang, kita tahu, betapa raut wajah kita tak lagi polos. Banyak guratan pikiran dan dosa yg kita catatkan.
Ahh, betapa usia sangat melenakan.
Pulanglah, pulang.
Dengan pulang kita bisa menyesap kopi yang dipanggang dari kebun sendiri.
Bisa menikmati nasi yang ditanak dari sawah sendiri.
Pulanglah, pulang.
Sebelum kita benar-benar pulang ke keabadian.
Di momen Syawal ini, belum telat rasanya saya menghaturkan maaf. Atas segala salah yg pernah dilakukan. Semoga kita semua kembali ke fitrah, sampai benar-benar “pulang” nanti. – PDA